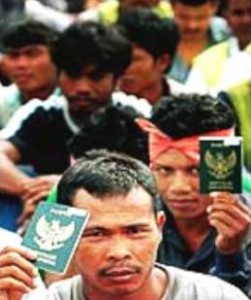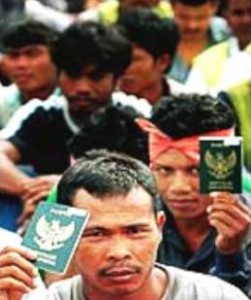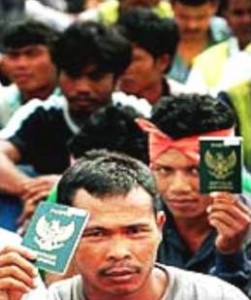Prilaku Miskin Buruh Migran
-M. Zainul Asror-
social development and walfare – UGM
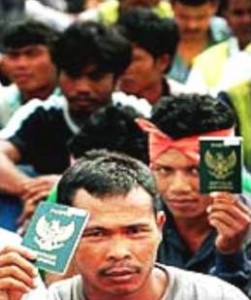 Selain munculnya kemiskinan yang disebabkan oleh negara atau sistem sosial masyarakat, lazimnya disebut sebagai fenomena pemiskinan struktural. Ada juga kemiskinan yang terjadi akibat dari kultur masyarakat. Dengan kata lain bahwa masyarakat miskin karena prilaku hidup mereka sendiri yang tidak berorientasi pada kesejahteraan.
Selain munculnya kemiskinan yang disebabkan oleh negara atau sistem sosial masyarakat, lazimnya disebut sebagai fenomena pemiskinan struktural. Ada juga kemiskinan yang terjadi akibat dari kultur masyarakat. Dengan kata lain bahwa masyarakat miskin karena prilaku hidup mereka sendiri yang tidak berorientasi pada kesejahteraan.
Prilaku hidup miskin tersebut dapat diberikan contoh seperti yang terjadi di Lombok Timur. Lombok Timur sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), merupakan salah satu kantong pengirim TKI terbesar di Indonesia. Kemiskinan dan ketiadaan lapangan kerja menjadi alasan utama masyarakat Lombok Timur berbondong-bondong ke luar negeri seperti Malaysia, Taiwan, Korea, Hongkong, Arab Saudi dan beberapa negara lain. Bahkan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian seringkali merasa penghasilan yang didapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada akhirnya petani-petani itupun ikut meninggalkan kerjanya untuk mencari penghidupan yang layak di negara jiran.
Fakta yang terjadi, banyaknya masyarakat Lombok Timur yang berkerja di luar negeri dengan gaji yang cukup tinggi ternyata tidak membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dinas ketenagakerjaan provinsi NTB yang bersumber dari data Bank Indonesia, ada terjadi peningkatan angka remitansi (pengiriman uang) dari tahun ke tahun. Namun, tingginya angka remitansi tersebut tidak berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Lombok Timur. Melihat kondisi tersebut tentu ada sesuatu yang menjadi penyebabnya, apa yang salah dengan masyarakat disana? dari penuturan beberapa informan dapat disimpulkan sementara bahwa kemiskinan yang terjadi adalah akibat prilaku hidup para buruh migran itu sendiri.
Ada dua jenis prilaku buruh migran Lombok Timur yang bisa diamati secara kasat mata. Pertama, sebagian buruh migran terutama yang ada di Malaysia mempunyai kebiasaan bekerja hanya pada waktu-waktu tertentu. Misalnya mereka bekerja mengumpulkan uang selama satu minggu, ketika uang yang terkumpul sudah dirasa cukup untuk bekal hidup beberapa waktu kedepan maka mereka tidak bekerja lagi. Baru bekerja lagi saat persediaan mereka akan habis. Pola bekerja seperti ini terus dilakukan berulang-ulang sehingga tidak pernah ada dampak perubahan terhadap kualitas kesejahteraan hidup.
Kedua, buruh migran dengan orientasi mengirim uang ke kampung. Sepintas, jika dibandingkan dengan prilaku pertama, prilaku ini tentu bisa dianggap lebih baik. Namun, kenyataannya tidak sepenuhnya benar. Misalnya buruh migran bekerja di Malaysia dengan kontrak waktu 2 tahun. Selama rentang waktu tersebut mereka memang bisa mengirim uang hasil bekerja dalam jumlah yang cukup besar, sehingga secara statistik meningkatkan angka remitansi cukup tinggi. Mereka bisa membayar hutang, merenovasi rumah, atau membeli kendaraan juga menabung. Ketika masa kontrak kerja habis mereka pulang kampung dan kembali menjadi pengangguran. Mirisnya lagi pola hidup ketika di kamung menjadi cenderung konsumtif. Pada akhirnya tabungan yang dikumpulkan selama sekian tahun habis untuk konsumsi barang-barang mewah atau mentraktir teman. Sementara tidak ada pemasukan sama sekali, ketika tabungan habis mereka bahkan tidak punya uang untuk kembali bekerja sebagai buruh migran, sehingga hutang jadi solusinya.
Begitu fenomena yang biasa terjadi di lingkungan keluarga buruh migran. Walaupun ada pengaruh bahwa kemiskinan mereka sebagai akibat dari kemiskinan struktural atau sistem sosial. Namun, faktor yang lebih dominan muncul karena kultur masyarakat atau prilaku hidup yang tidak mencerminkan pola hidup sejahtera.